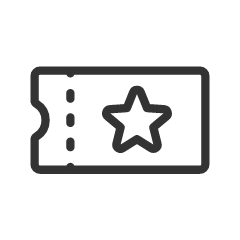Fan board

Enik Wahyuni
Uangku Hanya Satu Juta, Mas!
Part 1
***
"Barusan Ibu telpon, kita disuruh mampir dulu ke rumah Ibu sebelum kamu pulang ke orang tuamu, Meira."
"Apa maksudmu, Mas?" Kutatap lekat mata suamiku yang kian mendekat. Menajamkan pendengaran untuk memastikan sekali lagi.
"Ibu kangen sama Aretha, katanya. Nggak papa ya, kita mampir sebentar. Kurasa dua hari cukup lah di sana, habis itu kuantar kalian ke rumah Ibumu. Bagaimana? Kamu setuju, kan?"
"Tapi dua bulan yang lalu kita sudah pulang ke rumah Ibumu, Mas! Kamu udah janji, akan mengantarkan aku dan Aretha ke rumah Ibuku! Kenapa tujuannya jadi berbelok?" Aku terpekik, memandang Mas Bara dengan suara bergetar.
"Kan aku bilang, kita hanya dua hari di rumah Ibu. Setelah itu, kita langsung jalan ke rumah orang tuamu. Hanya untuk memberi ketenangan pada Ibu, Meira. Beliau kangen dengan Aretha, aku mohon kamu mengerti, ya?"
Aku mencelos. Entah berapa kali aku harus berusaha mengerti, tentang semua keinginan Mas Bara dan keluarganya. Sudah sering, kami pulang ke rumah ibu mertua. Namun aku sendiri harus menahan rindu dengan kedua orang tuaku selama tiga tahun.
Ya, selama tiga tahun. Setelah menikah dengan lelaki yang sekarang berada di depanku, aku tak merasakan hangat dekap kasih sayang orang tuaku sendiri. Hingga Aretha– anak semata wayangku– kini berumur dua tahun, belum sekalipun bertemu dengan kakek dan neneknya.
Miris, bukan?
"Pengertian seperti apa yang kamu inginkan?" Aku menunduk menahan hati yang sesak. Meremas dompet yang sejak tadi di tangan. "Uangku hanya satu juta, Mas! Rasanya tidak akan cukup, jika harus mampir dulu ke rumah Ibu. Aku tidak mau nanti habis, lalu gagal menemui kedua orang tuaku!" Sengaja kutekankan sedikit kata terakhir, agar Mas Bara berpikir.
Inilah alasan, mengapa aku selalu gagal untuk pulang ke kampung orang tuaku. Dua tahun mengalami pandemi, satu tahun setelahnya selalu tarik ulur tentang keuangan kami.
Uang dan tabungan Mas Bara seolah lenyap begitu saja jika sudah berada di tengah tengah keluarganya. Lalu, aku bisa apa? Jika Mas Bara sendiri memang menjadi tulang punggung dalam keluarga besar di sana.
Aku yang hanya seorang ibu rumah tangga, sengaja menyisihkan sedikit demi sedikit agar bisa pulang ke kampung orang tuaku. Dan sekarang sudah terkumpul satu juta nilainya, sudah cukuplah bagiku untuk menemui mereka yang tengah kurindukan di sana.
"Bagaimana, Mas, apa kamu bisa menjamin akan kepulanganku?" tekanku sekali lagi.
"Jangan khawatir, aku akan meminjam uang kantor untuk ongkos pulang. Minggu depan kita pulang, dan uangmu akan utuh sampai di kampung orang tuamu."
Aku menghela napas.
Di satu sisi, senang luar biasa karena Mas Bara sendiri sudah menjamin akan kepulanganku. Namun di sisi lain, rasa hati sedikit berat. Istri mana yang tega jika suami sendiri sampai berhutang demi menyenangkan orang-orang di sekelilingnya?
"Mas yakin?" tanyaku.
"Nggak jadi?" ledeknya.
Aku tersenyum. Jika berbicara soal orang tua masing-masing, selalu ada kemarahan dalam hati karena tidak rela.
Mas Bara bisa dengan mudah menghabiskan waktu dengan Ibunya. Sedangkan aku sendiri harus menahan kerinduan bertahun-tahun dengan kedua orang tuaku. Tetapi, mendengar seruannya tadi hatiku menjadi sedikit tenang. Sejauh ini karena memang keadaan yang memaksa untuk aku belum bisa memenuhi keinginan, bukan karena keengganan Mas Bara.
"Tidurlah, sudah malam. Besok aku akan mengajukan pinjaman, biar minggu depan langsung cair. Setelah itu, kita pulang."
Tak menjawab lagi, aku merebahkan diri di dekat Aretha. Sejenak, kutatap wajah lelaki yang menikahiku tiga tahun yang lalu. Terlihat kusut, walau senyum sedikit tersungging dari bibir manisnya.
Ada rasa berdosa karena telah mendesaknya, namun tiga tahun berlalu tanpa sedikitpun bersanding di antara Bapak dan Ibu itu terasa menyesakkan. Semoga rindu ini tersalurkan dan segera menemui mereka yang kusayangi di sana.
"Bapakmu kemarin habis sakit, Nduk. Pengen ketemu cucu satu-satunya yang belum pernah dilihatnya. Pulanglah, Nduk, sebentar saja. Kami ini sudah tua, tak sanggup rasanya jika harus jalan jauh ke Jakarta sana." Kembali terngiang ucapan Ibu di telepon kemarin, semakin membuat mataku memanas.
Hati mana yang tidak tersayat mendengarnya? Namun aku sendiri masih menempatkan suami pada posisi tertinggi karena memang keadaan yang membuatku sulit pulang. Maafkan aku, Pak, Bu, maafkan Meira yang belum bisa menjengukmu di sana.
***
Seminggu pun berlalu, akhirnya waktu yang kunanti pun tiba. Mobil yang dikendarai oleh Mas Bara berjalan perlahan meninggalkan tempat tinggal kami. Bersiap ke rumah mertua yang jaraknya juga lumayan.
Aku menghela napas. Mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi di rumah ibu mertua nanti. Apapun keadaannya, aku tak mau lagi lagi gagal untuk tetap pulang ke rumah Ibu. Semoga Mas Bara tidak mengingkari janjinya.
“Mama, kita mau ke lumah Nenek, ya? Asyiikk … Leta senang!” Aretha dengan suara gemasnya berceloteh.
Aku tersenyum menanggapi ucapan cadelnya. “Iya, Sayang. Nanti Aretha akan bertemu juga dengan nenek jauh, yang di sana. Retha kan punya dua nenek, yang belum Retha temui sama sekali.”
Mata bulatnya mengerjap, lucu sekali. Tak lama, wajah senang pun terpancar seiring dengan teriakan khasnya. “Yeeyy … Letha senang, Mama! Letha senang!” girangnya dengan badan mungil yang terus bergerak.
Aku memeluk tubuh mungil yang berada di pangkuanku. Bagaimana bisa Retha yang sudah berumur dua tahun, tapi neneknya, yang notabene cucu satu satunya, belum melihat tingkah lucunya seperti ini.
Mas Bara yang sedang menyetir, meremas tanganku pelan. “Jangan sedih!” ucapnya tanpa menoleh ke arahku.
Ah, semoga saja kau tahu apa yang menyebabkan aku sesak seperti ini, Mas. Semoga saja tidak ada kendala apapun, dari keluargamu nanti.
-
Matahari sudah mulai bersembunyi dalam peraduan, berganti dengan senja yang mulai terlihat memancar dari jauh sana. Aku menggerakkan badan karena terasa pegal, seiring dengan mobil yang terparkir tepat di halaman rumah ibu mertua.
Ya, kami sudah sampai di tempat tujuan, dan aku segera mengangkat Aretha yang tertidur di pangkuan.
“Bara … akhirnya, kamu sampai juga.” Ibu langsung mendatangi anak lelakinya dengan wajah yang begitu sumringah.
“Bu, apa kabar?” Aku menyalami mertua sambil menggendong Aretha.
“Baik, tapi jadi kurang baik kalau melihat kalian kecapean kayak gini. Istirahatlah! Lihatlah Aretha, sepertinya kelelahan. Kayak gini kamu mau maksain buat jalan jauh ke rumah orang tuamu. Pikir sekali lagi, Meira! Pikirkan keadaan Aretha, juga Bara. Janganlah terlalu egois.” Ibu langsung mengambil alih Aretha dalam gendonganku, lalu membawanya masuk.
Aku tersenyum getir. Sudah kuduga respon Ibu akan seperti ini. Dan ini bukan yang pertama kalinya.
“Sudah, jangan diambil hati. Ayo masuk!” Mas Bara merangkulku, mengajak untuk masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah, semua keponakannya sudah menunggu, dengan wajah yang begitu senang. Namun cukup membuatku sedikit sesak.
“Om Bara pulang! Yeeeyy … pasti bawa jajan banyak!”
“Om Bara pasti bawa mainan. Kemarin aku udah pesen, minta dibawain mobil-mobilan yang terkeren model terbaru.”
“Om … hapeku rusak. Beliin hape baru dong, Om! Aku jadi nggak bisa sekolah kalau hapenya rusak begini.”
Aku menghela napas. Mengamati wajah yang kusut walau memaksakan senyum di sana. Ingin mengetahui, jawaban apa yang diberikan oleh Mas Bara dengan permintaan para keponakannya itu.
******
Di Joylada udah bab 5. Yuk, langsung ke aplikasi. Free ya kak.
 1
1

Pusparani
Halo, Kak. Baca novelku BUKAN AKU TAK SETIA, ISTRI SANG JURAGAN (Gratis), dan beberapa novel lainnya, yuk. Siapa tahu suka.
Terima kasih.
 1
1

Selenoo
Haloo kak, aku ada cerita baru judulnya “Accidentally, Love You” silahkan mampir yaa kak, siapa tau suka hehhe 😍
 1
1

Okta Novita
Salam kenal, Kak. Kalau berkenan, boleh mampir ke ceritaku, ya 🤗
"DINGINNYA SUAMIKU - My Husband Secrets"
Kupandangi wajah tampan yang sudah lelap dalam tidurnya. Rasa damai memenuhi hati ini hanya saat mata Arsya Narendra—suamiku—sedang memejam. Dia terlihat seperti malaikat yang sudah menggenapi hidupku yang sempat hampa.
Lelaki berhidung bangir dengan kulit sawo matang itu telah menghalalkanku di depan Ayah tepat tiga bulan yang lalu. Rasanya masih belum percaya jika hubungan kami yang begitu mesra berubah sedingin bongkahan es.
“Kamu ngapain di sini?”
Aku terperanjat. Mas Arsya tiba-tiba membuka mata, padahal baru sekitar setengah jam dia tertidur. Gegas kubawa tubuh ini turun dari tempat tidur tanpa menjawab pertanyaannya. Aku diam, menunduk dalam posisi berdiri di samping tempat tidur. Tubuh ini gemetar dengan ujung jari saling meremas.
“Kamarmu di sebelah! Lupa?” tukasnya sedikit membentak.
“Ma–maaf, Mas. Ta–tadi ada tikus masuk kamarnya Mas Arsya,” jawabku gugup.
Mas Arsya menggeleng kasar, lalu menoleh ke arah pintu saat aku memandangnya. Sepertinya, itu isyarat agar aku keluar.
“Permisi, Mas,” pamitku sebelum melangkah ke luar kamar.
“Tunggu!” seru Mas Arsya. “Ambilkan saya minum dulu!” lanjutnya.
Aku pun berlalu dengan hati yang terasa kembali tersayat. Ingin rasanya mengaku kalah dan pergi jauh, tetapi seolah-olah ada yang berbisik agar aku bertahan. Entah dorongan dari mana dan untuk apa? Aku hanya ingin bahagia.
Segelas air putih kuangsurkan pada Mas Arsya yang sedang duduk bersandar di atas tempat tidur. Kemudian, aku segera pergi dari kamarnya. Gugup ini selalu menguasai jika bertemu muka dengan Mas Arsya karena kedua matanya yang menatapku benci. Air mata pun mulai mengalir membasahi pipi.
Semua berawal dari liburan bersama bulan lalu. Aku, Mas Arsya, dan Arumi—putri Mas Arsya dari istri pertamanya yang sudah meninggal—berencana untuk menghabiskan akhir pekan di rumah orang tuaku. Memang setelah menikah, kami belum sempat mengunjunginya sekali pun.
Ya, takdirku memang menjadi istri kedua dari Mas Arsya, tetapi bukan itu masalah sebenarnya. Keteledoranku saat menjaga Arumi yang masih berusia tiga tahun membuat gadis kecil itu tutup usia.
Saat itu, kami sedang menghentikan perjalanan untuk makan siang. Sementara Arumi merengek untuk dibelikan es krim. Aku pun pamit pada Mas Arsya untuk mengajak putrinya ke minimarket yang letaknya tepat di seberang restoran. Dan musibah itu terjadi. Arumi berlari cukup kencang hingga tanganku yang tadinya menggandeng tangannya terlepas. Gadis kecil itu tertabrak sepeda motor meskipun aku sudah mendapatkan tangannya lagi. Sebenarnya, aku juga terluka, tetapi Arumi tidak selamat.
***
Aku mendesah berat. Meskipun Mas Arsya masih memberikan nafkah lahir, tetapi aku seolah-olah bukan lagi seorang istri. Semua pekerjaan rumah sudah diambil alih oleh asisten rumah tangga, padahal sebelumnya, untuk urusan memasak diserahkan kepadaku. Dulu, dia sangat suka dengan apa pun yang aku masak, tapi sekarang, hanya sekadar menyebut namaku saja, dia enggan. Memang kesalahan yang kuperbuat tidak akan bisa dimaafkan.
“Yang sabar, Mbak. Mas Arsya pasti akan luluh lagi. Dia hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Setelah kehilangan mamanya Non Arumi, dia juga harus kehilangan putrinya.”
Perkataan Bik Narti justru membuat hati ini makin merasa bersalah. Aku memang bukan istri dan ibu yang baik. Aku, Amanda Nurita sudah membunuh putri dari suamiku sendiri.
Aku memejam sambil menarik napas panjang untuk mengurai sesak di dada yang terasa kian mengimpit. Bersamaan butiran kristal hangat yang keluar dari sudut mata, beban hati ini pun ikut meluruh meskipun hanya sedikit.
“Mbak Amanda jadi ke makam? Kalau jadi, saya ikut,” pinta Bi Narti, membuyarkan lamunanku.
“Jadi, Bi … jam delapan kita berangkat,” jawabku, lalu meninggalkannya ke kamar.
Hari ini, tepat empat puluh hari Arumi pergi. Namun, Mas Arsya tidak mau diadakan pengajian di rumah. Bahkan, dia selalu pergi lebih pagi dan pulang larut malam setiap harinya, di hari libur sekalipun. Untuk menghindariku pastinya.
'Aku mencintaimu, Mas. Namun, aku kesulitan untuk bertahan dalam pernikahan yang penuh kebencian.'
Tepat jam delapan pagi, aku dan Bi Narti berangkat menuju makam Arumi. Mendoakannya adalah yang utama. Dan setelah ini, mungkin aku akan melepaskan Mas Arsya dari beban. Dia tidak perlu lagi melihat wajahku, bahkan bayanganku di rumahnya.
Di depan pusara anak yang sudah sangat kusayangi, lutut ini melemas. Aku ingat betul kejadian di mana darah bersimbah di sekitar kepala Arumi sebelum aku ikut tak sadarkan diri. Aku tergugu dan tentunya masih saja menyalahkan diri sendiri yang teledor.
"Maafkan bunda, Nak. Bunda tidak bisa menjadi pengganti mamamu." Aku berucap lirih sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Air mata ini tidak boleh jatuh lagi meskipun tidak mampu ditahan.
Saat doa sedang kupanjatkan, suara keras membuatku kaget. Aku yang dalam posisi jongkok, langsung terjungkal ke belakang. Tentu aku terkejut bukan main
"Siapa yang mengizinkanmu kemari?! Kamu sudah membunuh anakku dan kamu masih beraninya kemari! Pergi! Jangan pernah memperlihatkan wajahmu lagi di depan makam Arumi!" Mas Arsya memekik dengan mata berkilat amarah.
Aku bangkit dibantu Bi Narti. Asisten rumah tangga itu tampak ketakutan melihat majikannya yang dipenuhi emosi. Tangan perempuan berusia sekitar lima puluh tahunan itu gemetar saat memegang lenganku.
"Ayo, kita pulang, Mbak. Kita nggak bisa apa-apa kalau Mas Arsya sudah marah. Bibi takut kalau Mbak Amanda jadi korban pelampiasannya lagi," bujuk Bi Narti dengan suara pelan.
Ya, memang sejak kepergian Arumi, Mas Arsya mulai bersikap dingin kepadaku. Beberapa kali bentakan dan cacian pernah kuterima hanya karena masuk ke kamar putrinya. Meskipun tidak pernah ada kekerasan fisik, Mas Arsya tampak menyesal setelahnya. Biarpun tidak ada kata maaf keluar dari mulutnya, aku tahu dari sorot matanya. Dia pasti langsung pergi dari rumah dan kembali di pagi hari, kemudian pergi lagi setelah membersihkan diri.
***
Aku mulai memasukkan pakaian ke dalam koper dan bersiap untuk pergi selagi Mas Arsy tidak di rumah dan Bi Narti sudah tidur. Gelapnya malam ini hampir sama dengan gelapnya nasibku. Meskipun hati ini berat meninggalkan Mas Arsya, tapi aku juga tidak mungkin tetap tinggal di tempat yang sudah menginginkan kepergianku.
Brak!
Aku menoleh seketika saat suara keras terdengar diikuti pintu kamar yang terbuka.
"Bagus," ucap Mas Arsya sambil bertepuk tangan. Ada seringai menakutkan di wajahnya saat menatapku.
"Ma–Mas." Aku perlahan berdiri dan beringsut mundur. Napas ini pun mulai pengap karena ketakutan yang tiba-tiba menyergap.
"Aku tidak akan membiarkanmu pergi dan bahagia sendiri setelah merenggut Arumi dariku." Mas Arsya mulai mendekat.
"Ma–maaf, Mas. Aku—" Tubuh ini terasa gemetar dan ucapanku pun terhenti saat jarak dengan laki-laki yang dikuasai emosi itu sangat dekat.
Tangan kanan Mas Arsya terangkat dan itu makin membuatku tidak bisa berkutik. Aku memilih menunduk dan memejam, menunggu apa yang akan terjadi setelahnya.
 1
1

Faida Risqiana
Assalamualaikum, salam kenal ya Kak, bila berkenan yuk mampir ke ceritaku, judulnya Kegagalan Membawa Berkah 🙏☺️
 1
1

Devi citra
Salam kenal kak 🙏 ,, jika berkenan silahkan baca cerita saya "Langit Senja" dan " Berbagi Cinta" 😊. Langsung klik profil saya
 1
1
Pengumuman
Sembunyikan postingan ini
Apakah kamu ingin sembunyikan postingan ini
Konfirm
แสดงโพสต์นี้
คุณต้องการแสดงโพสต์นี้ใช่หรือไม่
Konfirm
Hapus posting ini
Apakah kamu yakin ingin menghapus postingan ini ?
Hapus